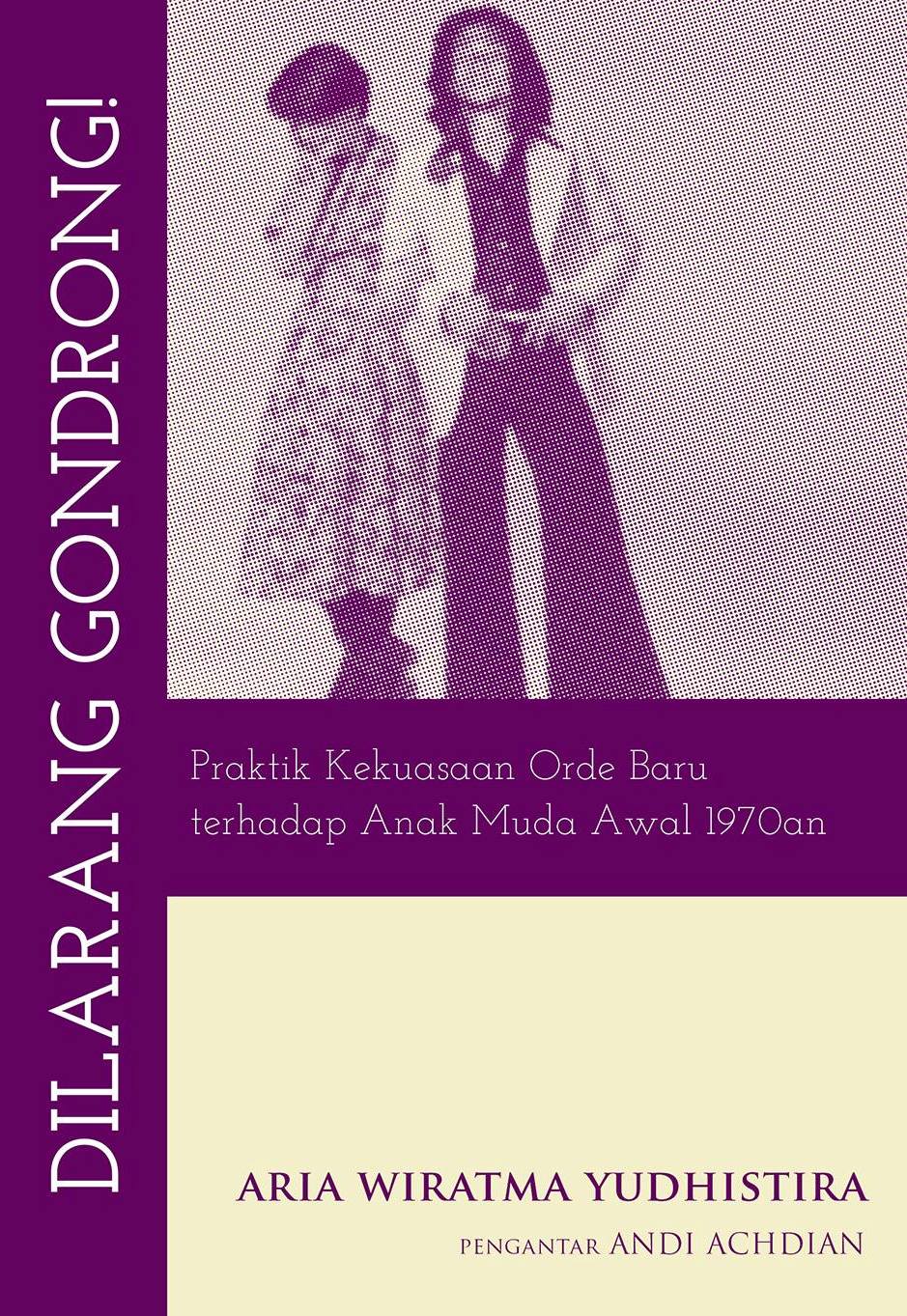Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970an
Rp.72.000,-
Rp.57.000
Diskon
Judul: Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Anak Muda Awal 1970an
Penulis: Aria Wiratma Yudhistira
Penerbit: Marjin Kiri, 2018
Tebal: 202 halaman
Kondisi: Bagus (Ori Segel)
Barangkali banyak yang tidak tahu bahwa gunting pernah menjadi alat utama Orde Baru untuk mengatur rakyatnya sendiri. Anda tak perlu heran. Ya, dalam dekade awal berdirinya rezim ini, kebijakan anti rambut gondrong pernah dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang dibarengi dengan hukum potong rambut di tempat bagi siapapun yang melanggarnya. Buku Aria Wiratman Yudhistira ini mencoba melakukan penelusuran terhadap episode sejarah yang menggelikan sekaligus mengenaskan tersebut.
Awal tahun 1970an menjadi masa yang menyibukkan bagi rezim untuk menyiapkan landasan kekuasaannya. Jargon “ekonomi sebagai panglima” dikeluarkan. Jargon yang diperkuat oleh strategi kebijakan ini dirancang sekelompok ilmuwan ekonomi yang kemudian dikenal dengan Mafia Berkeley. Pintu bagi investasi modal asing dibuka seluas-luasnya. Program “bersih lingkungan” dari unsur komunisme terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pembangunan ekonomi.
Sementara itu, dunia sedang dilanda gerakan perlawanan budaya anak-anak muda yang salah satunya mewujud dalam bentukhippies. Sebagaimana gerakan counter culture, hippies merupakan gagasan anak-anak muda tentang cara pandang mengenai kehidupan yang berbeda dengan yang dominan berlaku saat itu. Keberadaan mereka ditandai dengan tren fashion yang eksentrik. Rambut gondrong, sandal, mengenakan manik-manik bermacam-macam, serta kaum perempuannya tidak memakai bra.
Gerakan ini kemudian menyebar sampai ke Indonesia. Melalui media massa seperti surat kabar, radio, sampai film membuat anak-anak muda di negeri ini mulai mengikuti mode macam itu. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki akses terhadap informasi dan pendidikan. Anak-anak muda mulai berpakaian kedodoran, memanjangkan rambut, melakukan seks bebas dan menggunakan narkotika. Mereka kemudian tumbuh menjadi generasi yang apolitis dan sibuk mencari identitas diri.
Meskipun begitu, gejala tadi tidak diikuti oleh mayoritas anak muda negeri ini. Masih ada anak muda yang kritis terhadap pemerintah. Inilah mahasiswa-mahasiswa yang ironisnya turut serta menjadi motor terbentuknya Orde Baru. Mereka kecewa karena cita-cita mengenai negara yang ideal gagal dilaksanakan Orde Baru. Pembangunan yang terus digaungkan pun hanya menyentuh segelintir lapisan masyarakat saja. Kekecewaan ini kemudian ditunjukkan melalui serangkaian aksi demonstrasi yang menolak berbagai kebijakan pemerintah.
Perkembangan situasi tersebut rupanya membuat Orde Baru khawatir. Di satu sisi, mereka tidak memberikan toleransi terhadap mahasiswa yang semakin bertindak radikal menentang kebijakan. Di sisi lain, rezim ketakutan karena anak-anak mereka mulai terpengaruh gaya hidup hippies. Seperti diberitakan media cetak saat itu, kasus kenakalan remaja memberi kesan implisit bahwa mereka berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Karena itu, kebijakan anti rambut gondrong dikeluarkan. Kebijakan yang menjadi upaya melindungi anak-anak mereka sendiri sekaligus melakukan kontrol terhadap anak-anak muda lain yang kritis (baca: mahasiswa).
Kebijakan yang dalam kacamata saat ini bisa dikatakan menggelikan ini tidak main-main. Pelarangan rambut gondrong dilakukan secara sistematis melalui dua hal. Pertama, melalui kuasa wacana. Rambut gondrong dicitrakan dengan negatif dalam berita yang muncul di media massa. Tak perlu heran jika judul-judul berita seperti “7 Pemuda Gondrong Merampok Bis Kota”, “6 Pemuda Gondrong Perkosa 2 Wanita”, “Disambar Si Gondrong” menjadi sesuatu yang biasa (hal 104). Apa yang dilukiskan dalam berita itu menunjukkan bagaimana citra rambut gondrong dibentuk. Apalagi, rambut gondrong biasanya diikuti dengan kata-kata seperti “merampok”, “memperkosa”, “merampas”, dan sebagainya.
Kedua, tindakan fisik dilakukan secara sistematis oleh pemerintah melalui serangkaian peraturan yang ditindaklanjuti oleh istitusi-institusi negara di daerah. Menhankam/Pangab mengirim radiogram No. SHK/1046/IX/73 kepada seluruh jajarannya. Isinya, anggota ABRI dan karyawan sipil yang bekeraja di lingkungan militer beserta keluarganya dilarang berambut gondrong. Razia dan pelarangan rambut gondrong kemudian digelar di jalan-jalan.
Akhir 1966, 150 remaja berambut gondrong terjaring operasi yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan ABRI. Razia di Jakarta pada awal 1968 barangkali menjadi aksi yang paling menghebohkan sebab instruksi tersebut langsung dikeluarkan oleh Gubernur Ali Sadikin. Di Yogyakarta, lokakarya yang dilakukan kepala sekolah SMP dan SMA se-Yogyakarta menghasilkan keputusan untuk melarang siswa sekolah tersebut berambut gondrong. Dikeluarkan dari seolah menjadi hukuman bagi siswa yang nekat melanggar.
Seolah belum cukup, Gubernur Sumatera Utara Marah Halim bahkan membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan RambutGondrong yang disingkat menjadi Bakorperagon. Badan ini beranggotakan pejabat daerah tingkat 1 ditambah wakil kwartir Pramuka provinsi Sumatera Utara. Tujuannya, membasmi tata cara pemeliharaan rambut yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan Indonesia (halaman 119). Setelah badan ini dibentuk, semua institusi pemerintah daerah dilarang untu melayani orang-orang berambut gondrong. Pada Oktober 1973, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro bahkan mengatakan bahwa rambut gondrong membuat pemuda menjadi onverschillig alias acuh tak acuh.
Sebagai sebuah karya sejarah, buku ini patut diapresiasi karena dengan lugas menggambarkan bagaimana praktik kekuasaan Orde Baru dijalankan sampai pada hal yang privat, rambut. Sayangnya, proses malih rupa karya yang awalnya merupakan skripsi menjadi buku ini kurang halus. Ini membuat penjelasan begitu berputar-putar dengan teori dan latar belakang sebelum menuju kebijakan anti rambut gondrong.
Terlepas dari hal tersebut, buku ini mengingatkan bagaimana pratik kekuasaan tetap menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi individu. Persis seperti yang diucapkan Foucault bahwa kekuasaan menjadi alat untuk menormalisasi individu-individu melalui serangkain norma dan peraturan yang ditetapkan. Dan yang lebih berbahaya, praktik kekuasaan kini tak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga masyarakat sipil. Sebuah ancaman yang serius.
Pesan Sekarang
Penulis: Aria Wiratma Yudhistira
Penerbit: Marjin Kiri, 2018
Tebal: 202 halaman
Kondisi: Bagus (Ori Segel)
Barangkali banyak yang tidak tahu bahwa gunting pernah menjadi alat utama Orde Baru untuk mengatur rakyatnya sendiri. Anda tak perlu heran. Ya, dalam dekade awal berdirinya rezim ini, kebijakan anti rambut gondrong pernah dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang dibarengi dengan hukum potong rambut di tempat bagi siapapun yang melanggarnya. Buku Aria Wiratman Yudhistira ini mencoba melakukan penelusuran terhadap episode sejarah yang menggelikan sekaligus mengenaskan tersebut.
Awal tahun 1970an menjadi masa yang menyibukkan bagi rezim untuk menyiapkan landasan kekuasaannya. Jargon “ekonomi sebagai panglima” dikeluarkan. Jargon yang diperkuat oleh strategi kebijakan ini dirancang sekelompok ilmuwan ekonomi yang kemudian dikenal dengan Mafia Berkeley. Pintu bagi investasi modal asing dibuka seluas-luasnya. Program “bersih lingkungan” dari unsur komunisme terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pembangunan ekonomi.
Sementara itu, dunia sedang dilanda gerakan perlawanan budaya anak-anak muda yang salah satunya mewujud dalam bentukhippies. Sebagaimana gerakan counter culture, hippies merupakan gagasan anak-anak muda tentang cara pandang mengenai kehidupan yang berbeda dengan yang dominan berlaku saat itu. Keberadaan mereka ditandai dengan tren fashion yang eksentrik. Rambut gondrong, sandal, mengenakan manik-manik bermacam-macam, serta kaum perempuannya tidak memakai bra.
Gerakan ini kemudian menyebar sampai ke Indonesia. Melalui media massa seperti surat kabar, radio, sampai film membuat anak-anak muda di negeri ini mulai mengikuti mode macam itu. Terlebih lagi bagi mereka yang memiliki akses terhadap informasi dan pendidikan. Anak-anak muda mulai berpakaian kedodoran, memanjangkan rambut, melakukan seks bebas dan menggunakan narkotika. Mereka kemudian tumbuh menjadi generasi yang apolitis dan sibuk mencari identitas diri.
Meskipun begitu, gejala tadi tidak diikuti oleh mayoritas anak muda negeri ini. Masih ada anak muda yang kritis terhadap pemerintah. Inilah mahasiswa-mahasiswa yang ironisnya turut serta menjadi motor terbentuknya Orde Baru. Mereka kecewa karena cita-cita mengenai negara yang ideal gagal dilaksanakan Orde Baru. Pembangunan yang terus digaungkan pun hanya menyentuh segelintir lapisan masyarakat saja. Kekecewaan ini kemudian ditunjukkan melalui serangkaian aksi demonstrasi yang menolak berbagai kebijakan pemerintah.
Perkembangan situasi tersebut rupanya membuat Orde Baru khawatir. Di satu sisi, mereka tidak memberikan toleransi terhadap mahasiswa yang semakin bertindak radikal menentang kebijakan. Di sisi lain, rezim ketakutan karena anak-anak mereka mulai terpengaruh gaya hidup hippies. Seperti diberitakan media cetak saat itu, kasus kenakalan remaja memberi kesan implisit bahwa mereka berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Karena itu, kebijakan anti rambut gondrong dikeluarkan. Kebijakan yang menjadi upaya melindungi anak-anak mereka sendiri sekaligus melakukan kontrol terhadap anak-anak muda lain yang kritis (baca: mahasiswa).
Kebijakan yang dalam kacamata saat ini bisa dikatakan menggelikan ini tidak main-main. Pelarangan rambut gondrong dilakukan secara sistematis melalui dua hal. Pertama, melalui kuasa wacana. Rambut gondrong dicitrakan dengan negatif dalam berita yang muncul di media massa. Tak perlu heran jika judul-judul berita seperti “7 Pemuda Gondrong Merampok Bis Kota”, “6 Pemuda Gondrong Perkosa 2 Wanita”, “Disambar Si Gondrong” menjadi sesuatu yang biasa (hal 104). Apa yang dilukiskan dalam berita itu menunjukkan bagaimana citra rambut gondrong dibentuk. Apalagi, rambut gondrong biasanya diikuti dengan kata-kata seperti “merampok”, “memperkosa”, “merampas”, dan sebagainya.
Kedua, tindakan fisik dilakukan secara sistematis oleh pemerintah melalui serangkaian peraturan yang ditindaklanjuti oleh istitusi-institusi negara di daerah. Menhankam/Pangab mengirim radiogram No. SHK/1046/IX/73 kepada seluruh jajarannya. Isinya, anggota ABRI dan karyawan sipil yang bekeraja di lingkungan militer beserta keluarganya dilarang berambut gondrong. Razia dan pelarangan rambut gondrong kemudian digelar di jalan-jalan.
Akhir 1966, 150 remaja berambut gondrong terjaring operasi yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan ABRI. Razia di Jakarta pada awal 1968 barangkali menjadi aksi yang paling menghebohkan sebab instruksi tersebut langsung dikeluarkan oleh Gubernur Ali Sadikin. Di Yogyakarta, lokakarya yang dilakukan kepala sekolah SMP dan SMA se-Yogyakarta menghasilkan keputusan untuk melarang siswa sekolah tersebut berambut gondrong. Dikeluarkan dari seolah menjadi hukuman bagi siswa yang nekat melanggar.
Seolah belum cukup, Gubernur Sumatera Utara Marah Halim bahkan membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan RambutGondrong yang disingkat menjadi Bakorperagon. Badan ini beranggotakan pejabat daerah tingkat 1 ditambah wakil kwartir Pramuka provinsi Sumatera Utara. Tujuannya, membasmi tata cara pemeliharaan rambut yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan Indonesia (halaman 119). Setelah badan ini dibentuk, semua institusi pemerintah daerah dilarang untu melayani orang-orang berambut gondrong. Pada Oktober 1973, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro bahkan mengatakan bahwa rambut gondrong membuat pemuda menjadi onverschillig alias acuh tak acuh.
Sebagai sebuah karya sejarah, buku ini patut diapresiasi karena dengan lugas menggambarkan bagaimana praktik kekuasaan Orde Baru dijalankan sampai pada hal yang privat, rambut. Sayangnya, proses malih rupa karya yang awalnya merupakan skripsi menjadi buku ini kurang halus. Ini membuat penjelasan begitu berputar-putar dengan teori dan latar belakang sebelum menuju kebijakan anti rambut gondrong.
Terlepas dari hal tersebut, buku ini mengingatkan bagaimana pratik kekuasaan tetap menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi individu. Persis seperti yang diucapkan Foucault bahwa kekuasaan menjadi alat untuk menormalisasi individu-individu melalui serangkain norma dan peraturan yang ditetapkan. Dan yang lebih berbahaya, praktik kekuasaan kini tak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga masyarakat sipil. Sebuah ancaman yang serius.