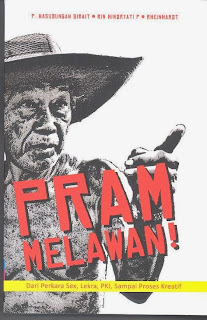Jual Buku Pram Melawan!: Dari Perkara Sex, Lekra, PKI, sampai Proses Kreatif
Judul: Pram Melawan!: Dari Perkara Sex, Lekra, PKI, sampai Proses Kreatif
Penulis: P. Hasudungan Sirait, Rin Hindrayati P, Rheinhardt
Penerbit: Nalar, 2011
Tebal: 542 halaman
Kondisi: Stok lama (Bagus)
Harga: Rp. 150.000 (blm ongkir)
SMS/WA: 085225918312
Pernahkan Pram melihat hantu? Di tengah serbuan kuntilanak, genderuwo, dalam produk film dan sinetron kita hari ini, pertanyaan itu tentu menarik. Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan besar, yang menolak semua hal tak rasional. Percayakah dia pada sesuatu yang gaib?
Hantu, bagi Pram, tak lebih dari fosfor yang keluar dari tubuh mati membusuk. Dia, misalnya, mengaku melihat apa yang dikira orang hantu. Diceritakan, saat masih tinggal di Tanah Abang, Jakarta, Pram pernah mengalami hal aneh. Di rumah itu istrinya kerap diganggu makhluk halus, sampai berteriak-teriak, dan lari ketakutan.
Suatu malam Pram tidur di kamar itu sendirian. “Malam itu dari lubang masuk cahaya api”, ujarnya. Berbentuk pelangi, cahaya itu memutar, dan mendekati dia. Pram menggertak. “Pergi, ke luar!” Cahaya api itu pun lenyap. Lalu percayakah Pram? “Saya nggak mau percaya,” ujarnya. Bagi dia, hal-hal gaib itu tak berguna, dan menghambat kemajuan berpikir.
Ada banyak kisah yang jarang kita dengar dari Pram, tertuang di buku setebal 502 halaman ini. Pram bercerita segi paling pribadi, dari pengalaman mistik sampai seks. Dia misalnya, pernah dipasok ilmu kebal oleh seorang dukun, saat menjadi gerilyawan masa revolusi kemerdekaan. Dalam ritual itu, lehernya digorok parang oleh si dukun, dan tak mempan. Tapi, dia toh tetap tak percaya. Anehnya, seperti diakui oleh Pram, saat diberondong senapan mesin oleh serdadu Inggris di pertempuran Bekasi-Kranji, dia selamat.
Atau hal lain: sewaktu remaja dia penah diajari ibunya ilmu patirogo, semacam jiwa keluar dari tubuh untuk bertemu para arwah. Dia sempat juga berlatih ilmu itu. Pram mengaku, kelak dia melakoninya kembali saat jiwanya sedang krisis sebagai tahanan Orde Baru, di penjara Salemba. Soal seks, kita bisa tercengang membaca kisah Pram, mengapa dia ditaksir perempuan Barat, alasannya berselingkuh, dan sampai tidur dengan mereka.
Buku ini menarik karena dia seperti menghidupkan kembali Pram, dan pikirannya. Semangat, dan sifat keras kepalanya kepada kekuasaan yang menindas, terasa dalam setiap topik percakapan. Dibagi dalam tujuh bab, Cerita I sampai Cerita VII, beragam soal dikupas. Selain ihwal mistik dan seks itu, Pram juga bicara proses kreatifnya sebagai pengarang, tentang PKI, Lekra, Aceh, Papua, presiden, sastra, terorisme, sejarah, film dan sebagainya. Model tanya jawab sengaja dipilih agar tak merusak gaya khas Pram, yang berbicara dengan diksi, dan alur yang khas.
Percakapan itu juga menjadi semacam perjumpaan dua generasi. Penulis buku ini adalah dua wartawan, Hasudungan Sirait dan Rin Hindryati, serta seorang aktivis mahasiswa UI, Rheinhardt Sirait. Has, panggilan akrab Hasudungan, bercerita seperti halnya banyak mahasiswa era 80an, dia adalah pengagum Pram. Pada masa bukunya dilarang, mereka membacanya diam-diam.
Seperti juga Has, bagi generasi lebih muda dari angkatan 90an, yang kelak menjadi penjungkal kediktatoran, Pram adalah ikon pemantik keberanian. Bagi mereka, tak ada sastrawan di republik ini yang novelnya dibaca dengan tangan gemetar seperti karya Pram. Karyanya mampu menyuntik keberanian melawan kediktatoran. “Buku ini diawali rasa hormat pada Pram,” ujar Has.
Itu sebabnya, nyaris seluruh pertanyaan yang diajukan, seperti mewakili keingintahuan generasi baru pasca kediktatoran, tentang suatu masa gelap, dan dulu tak terjamah, semisal pembantaian komunis pasca 1965. Dia juga bicara kekacauan politik dari para pemimpin republik ini dari setiap zaman.
Para penulis buku ini melakukan wawancara intensif, dari 2001 sampai 2004. Segala percakapan dalam ratusan kali tatap muka itu direkam. Setiap pekan dalam kurun waktu itu, kecuali di 2003 dan 2004, mereka menyambangi Pram di rumahnya, di Bojong Gede. Itu sebabnya, wawancara mengalir bak obrolan harian. Has lalu memilah dan menyuntingnya. Dia mengatur rapi bab sesuai topik pembicaraan.
Pada Cerita I, Pram membuka rahasia proses kreatifnya sebagai pengarang. Dia tak percaya bakat, dan juga teknik. Dia percaya pada pengalaman hidup sebagai sumur bahan cerita. Baginya, menulis adalah perkara keberanian. “Menulis itu persoalan individual. Seperti orang masuk ke rimba belantara, dia sendirian. Memutuskan sendirian”, kata Pram (h.4).
Karena semua pengalaman hidup adalah bahan bagi pengarang, maka proses kreatif baginya adalah kelihaian membuka-tutup klep bawah sadar. Setiap pribadi membawa bagasi pengalaman yang kaya, dan semua itu berdiam di bawah sadar. Setiap orang juga mewarisi jaring laba-laba pengalaman ribuan tahun dari manusia sebelumnya.
Menulis, bagi Pram, adalah juga sebuah proses biokimia. Pengarang menggali bahan di bawah sadar, meneteskannya dengan pemikiran, dan mengolahnya kembali menjadi cerita. Pram menganggap semua tulisannya adalah anak rohani, yang boleh ditafsirkan sebebasnya oleh pembaca. Setiap karya sastra itu hidup bagi dirinya sendiri, tak perlu lagi campur tangan pengarang.
Kesan sendirian, dan melawan, itu terasa hampir dalam setiap bagian buku ini. Dia mengatakan karakternya itu adalah hasil tempaan ibunya, yang mendidiknya agar tak menjadi orang yang meminta-minta. Bagi Pram belia, hal itu cukup kuat membekas. “Jadilah majikan atas dirimu sendiri,” demikian pesan ibunda Pram. Kelak Pram membawa pesan itu dalam melakoni hidupnya. Dia tak ingin didikte siapapun, tidak oleh kekuasaan politik, dan juga agama.
Satu fragmen menarik dari buku ini adalah napak tilas Pram tatkala dia pulang ke kampungnya di Blora, Jawa Tengah, pada 2003. Pram sempat mengujungi kembali lokasi sekolah Instituut Boedi Oetomo (IBO) tempat ayahnya dulu mengajar. Tempat itu sudah menjadi SMP 5 Blora, dan dia menolak masuk ke dalamnya, karena kayu jati yang menjadi tiang sekolah itu telah hilang, ditilep entah siapa.
Di Blora, dia juga mengajak penulis menilik kembali pohon jarak di sebuah pekuburan, tempat dia pernah merasa terhina oleh perkataan ayahnya. Dia dibilang bodoh, dan dihukum mengulang di kelas 7 SD meskipun dia telah lulus. Tapi Pram kecewa, lokasi pekuburan itu telah jadi perumahan. Dia lalu menceritakan kembali kisah pedih zaman kanak-kanak itu, seperti peristiwa itu baru saja berlalu. Lalu, Pram pun menangis (h.387).
Pram memang telah meninggal lima tahun silam. Tapi kelugasan dia bicara apa adanya, menjadikan buku ini penting bagi siapa pun yang ingin menyelami jagad batin pengarang besar Indonesia itu. Pram telah melakoni hidupnya dengan berani berjiwa merdeka, dan menolak menjadi pecundang yang hipokrit.
Nezar Patria, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Penulis: P. Hasudungan Sirait, Rin Hindrayati P, Rheinhardt
Penerbit: Nalar, 2011
Tebal: 542 halaman
Kondisi: Stok lama (Bagus)
Harga: Rp. 150.000 (blm ongkir)
SMS/WA: 085225918312
Pernahkan Pram melihat hantu? Di tengah serbuan kuntilanak, genderuwo, dalam produk film dan sinetron kita hari ini, pertanyaan itu tentu menarik. Pramoedya Ananta Toer, seorang sastrawan besar, yang menolak semua hal tak rasional. Percayakah dia pada sesuatu yang gaib?
Hantu, bagi Pram, tak lebih dari fosfor yang keluar dari tubuh mati membusuk. Dia, misalnya, mengaku melihat apa yang dikira orang hantu. Diceritakan, saat masih tinggal di Tanah Abang, Jakarta, Pram pernah mengalami hal aneh. Di rumah itu istrinya kerap diganggu makhluk halus, sampai berteriak-teriak, dan lari ketakutan.
Suatu malam Pram tidur di kamar itu sendirian. “Malam itu dari lubang masuk cahaya api”, ujarnya. Berbentuk pelangi, cahaya itu memutar, dan mendekati dia. Pram menggertak. “Pergi, ke luar!” Cahaya api itu pun lenyap. Lalu percayakah Pram? “Saya nggak mau percaya,” ujarnya. Bagi dia, hal-hal gaib itu tak berguna, dan menghambat kemajuan berpikir.
Ada banyak kisah yang jarang kita dengar dari Pram, tertuang di buku setebal 502 halaman ini. Pram bercerita segi paling pribadi, dari pengalaman mistik sampai seks. Dia misalnya, pernah dipasok ilmu kebal oleh seorang dukun, saat menjadi gerilyawan masa revolusi kemerdekaan. Dalam ritual itu, lehernya digorok parang oleh si dukun, dan tak mempan. Tapi, dia toh tetap tak percaya. Anehnya, seperti diakui oleh Pram, saat diberondong senapan mesin oleh serdadu Inggris di pertempuran Bekasi-Kranji, dia selamat.
Atau hal lain: sewaktu remaja dia penah diajari ibunya ilmu patirogo, semacam jiwa keluar dari tubuh untuk bertemu para arwah. Dia sempat juga berlatih ilmu itu. Pram mengaku, kelak dia melakoninya kembali saat jiwanya sedang krisis sebagai tahanan Orde Baru, di penjara Salemba. Soal seks, kita bisa tercengang membaca kisah Pram, mengapa dia ditaksir perempuan Barat, alasannya berselingkuh, dan sampai tidur dengan mereka.
Buku ini menarik karena dia seperti menghidupkan kembali Pram, dan pikirannya. Semangat, dan sifat keras kepalanya kepada kekuasaan yang menindas, terasa dalam setiap topik percakapan. Dibagi dalam tujuh bab, Cerita I sampai Cerita VII, beragam soal dikupas. Selain ihwal mistik dan seks itu, Pram juga bicara proses kreatifnya sebagai pengarang, tentang PKI, Lekra, Aceh, Papua, presiden, sastra, terorisme, sejarah, film dan sebagainya. Model tanya jawab sengaja dipilih agar tak merusak gaya khas Pram, yang berbicara dengan diksi, dan alur yang khas.
Percakapan itu juga menjadi semacam perjumpaan dua generasi. Penulis buku ini adalah dua wartawan, Hasudungan Sirait dan Rin Hindryati, serta seorang aktivis mahasiswa UI, Rheinhardt Sirait. Has, panggilan akrab Hasudungan, bercerita seperti halnya banyak mahasiswa era 80an, dia adalah pengagum Pram. Pada masa bukunya dilarang, mereka membacanya diam-diam.
Seperti juga Has, bagi generasi lebih muda dari angkatan 90an, yang kelak menjadi penjungkal kediktatoran, Pram adalah ikon pemantik keberanian. Bagi mereka, tak ada sastrawan di republik ini yang novelnya dibaca dengan tangan gemetar seperti karya Pram. Karyanya mampu menyuntik keberanian melawan kediktatoran. “Buku ini diawali rasa hormat pada Pram,” ujar Has.
Itu sebabnya, nyaris seluruh pertanyaan yang diajukan, seperti mewakili keingintahuan generasi baru pasca kediktatoran, tentang suatu masa gelap, dan dulu tak terjamah, semisal pembantaian komunis pasca 1965. Dia juga bicara kekacauan politik dari para pemimpin republik ini dari setiap zaman.
Para penulis buku ini melakukan wawancara intensif, dari 2001 sampai 2004. Segala percakapan dalam ratusan kali tatap muka itu direkam. Setiap pekan dalam kurun waktu itu, kecuali di 2003 dan 2004, mereka menyambangi Pram di rumahnya, di Bojong Gede. Itu sebabnya, wawancara mengalir bak obrolan harian. Has lalu memilah dan menyuntingnya. Dia mengatur rapi bab sesuai topik pembicaraan.
Pada Cerita I, Pram membuka rahasia proses kreatifnya sebagai pengarang. Dia tak percaya bakat, dan juga teknik. Dia percaya pada pengalaman hidup sebagai sumur bahan cerita. Baginya, menulis adalah perkara keberanian. “Menulis itu persoalan individual. Seperti orang masuk ke rimba belantara, dia sendirian. Memutuskan sendirian”, kata Pram (h.4).
Karena semua pengalaman hidup adalah bahan bagi pengarang, maka proses kreatif baginya adalah kelihaian membuka-tutup klep bawah sadar. Setiap pribadi membawa bagasi pengalaman yang kaya, dan semua itu berdiam di bawah sadar. Setiap orang juga mewarisi jaring laba-laba pengalaman ribuan tahun dari manusia sebelumnya.
Menulis, bagi Pram, adalah juga sebuah proses biokimia. Pengarang menggali bahan di bawah sadar, meneteskannya dengan pemikiran, dan mengolahnya kembali menjadi cerita. Pram menganggap semua tulisannya adalah anak rohani, yang boleh ditafsirkan sebebasnya oleh pembaca. Setiap karya sastra itu hidup bagi dirinya sendiri, tak perlu lagi campur tangan pengarang.
Kesan sendirian, dan melawan, itu terasa hampir dalam setiap bagian buku ini. Dia mengatakan karakternya itu adalah hasil tempaan ibunya, yang mendidiknya agar tak menjadi orang yang meminta-minta. Bagi Pram belia, hal itu cukup kuat membekas. “Jadilah majikan atas dirimu sendiri,” demikian pesan ibunda Pram. Kelak Pram membawa pesan itu dalam melakoni hidupnya. Dia tak ingin didikte siapapun, tidak oleh kekuasaan politik, dan juga agama.
Satu fragmen menarik dari buku ini adalah napak tilas Pram tatkala dia pulang ke kampungnya di Blora, Jawa Tengah, pada 2003. Pram sempat mengujungi kembali lokasi sekolah Instituut Boedi Oetomo (IBO) tempat ayahnya dulu mengajar. Tempat itu sudah menjadi SMP 5 Blora, dan dia menolak masuk ke dalamnya, karena kayu jati yang menjadi tiang sekolah itu telah hilang, ditilep entah siapa.
Di Blora, dia juga mengajak penulis menilik kembali pohon jarak di sebuah pekuburan, tempat dia pernah merasa terhina oleh perkataan ayahnya. Dia dibilang bodoh, dan dihukum mengulang di kelas 7 SD meskipun dia telah lulus. Tapi Pram kecewa, lokasi pekuburan itu telah jadi perumahan. Dia lalu menceritakan kembali kisah pedih zaman kanak-kanak itu, seperti peristiwa itu baru saja berlalu. Lalu, Pram pun menangis (h.387).
Pram memang telah meninggal lima tahun silam. Tapi kelugasan dia bicara apa adanya, menjadikan buku ini penting bagi siapa pun yang ingin menyelami jagad batin pengarang besar Indonesia itu. Pram telah melakoni hidupnya dengan berani berjiwa merdeka, dan menolak menjadi pecundang yang hipokrit.
Nezar Patria, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI)